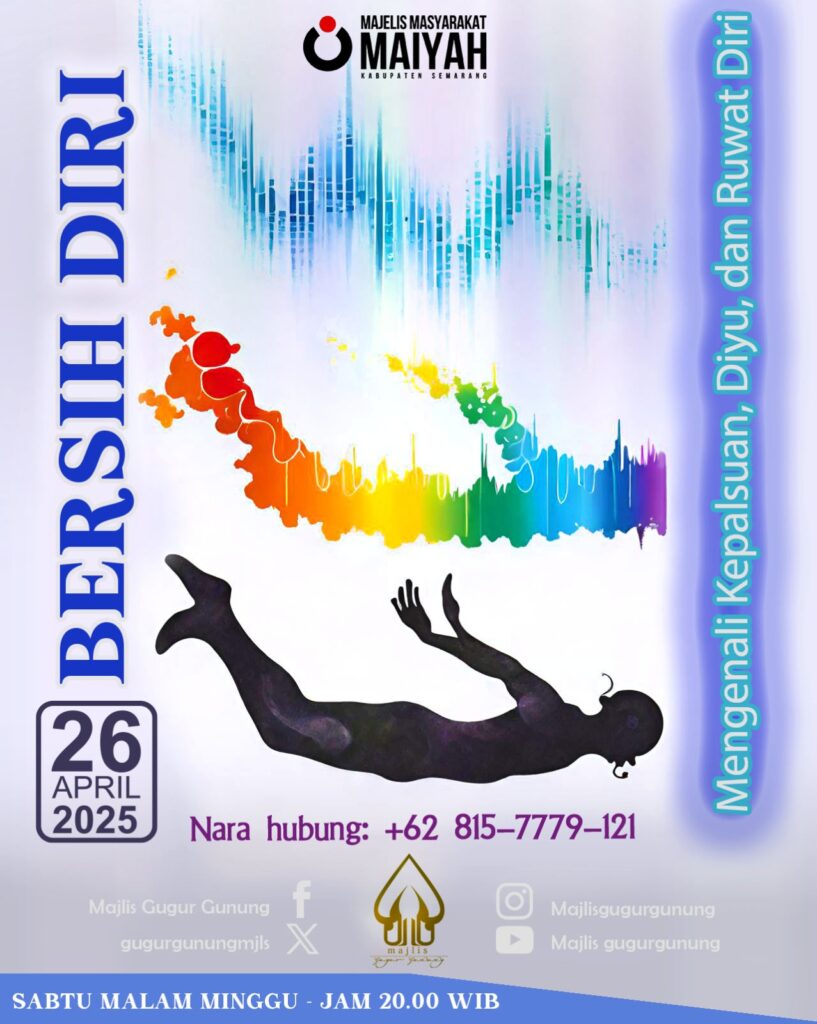Di setiap zaman, manusia selalu berjalan di antara dua jalur, keluarga gugurgunung menyebutnya: Shirathun Nubuwwah dan shirothut talbis. Sejak manusia pertama diturunkan, Allah telah membekali mereka dengan jalur cahaya. Bukan manusia setengah monyet, bukan makhluk liar yang buta arah, tapi makhluk berakal dan beradab, perintis peradaban awal yang mewarisi Wahyu langsung dari An Nuur. Nabi Adam, Nabi Syits, Nabi Idris, Nabi Nuh, hingga Nabi Ibrahim AS. Pewarisan ini terus berlangsung hingga Rasulullah Muhammad SAW. Para Nabi dan Rasul adalah pelopor yang menjaga titian cahaya agar manusia tetap terhubung pada sumber asalnya.
Namun, seiring peradaban berkembang, tumbuh pula nafsu, akal, dan hasrat yang menuntut kebebasan. Dari kebebasan itu lahirlah kelompok Maghdhub — golongan yang tahu kebenaran Shirathal Mustaqiim, tapi sengaja menyeleweng demi kepentingan nista. Mereka membangun Talbis, sistem ilusi yang membungkus kebatilan dalam kemasan suci. Samiri, Firaun, Haman, hingga Bal’am bin Baura adalah contoh pengkhianat cahaya yang bertransformasi menjadi arsitek kegelapan di zamannya.
Ketika Talbis makin kuat, mayoritas manusia yang tak paham hakikat terseret arus. Mereka menjadi kaum Dhaliin — orang-orang yang tersesat bukan karena niat buruk, tapi karena disorientasi dan ketidaktahuan akan jalur cahaya. Mereka hidup dalam Simulakra, ilusi yang didandani sebagai kebenaran, dipropagandakan lewat pemuka opini, tokoh sosial, atau ritual-ritual kosong yang memutuskan hubungan mereka dengan An Nuur.
Di sinilah letak pentingnya Azimat Ojo Maghdub. Sebuah pagar hidup yang bukan sekadar mantra, melainkan kesadaran aktif menjaga diri, keluarga, dan keturunan dari keruhnya arus ilusi zaman. Karena ketika manusia terputus dari jalur cahaya, maka hidupnya akan dipenuhi keraguan, ketakutan, dan kebingungan. Mereka jadi boneka di tangan Talbis, dipermainkan dalam permainan nista yang tak pernah mereka pahami.
Pitulungan — pertolongan dari An Nuur — hanya turun kepada mereka yang tetap menjaga jalur cahaya di hatinya. Sedang pitung turunan bukan sekadar soal darah keturunan, tapi soal warisan resonansi nilai yang jernih dan terang, yang kelak menjadi benteng bagi anak-cucu agar tak mudah hanyut dalam kegelapan arus. Itulah azimat sejati: menjaga garis cahaya hingga tujuh keturunan, bukan hanya hidup untuk hari ini.
Di akhir zaman, manusia yang bertahan bukanlah yang paling kuat, bukan yang paling kaya, apalagi yang paling terkenal. Tapi mereka yang tetap jernih pikirannya, bening hatinya, dan kokoh pijakannya di atas jalur cahaya. Mereka ini yang akan tetap bisa membedakan mana titian cahaya, mana ilusi Simulakra. Mana pertolongan An Nuur, mana bujukan nista Talbis.
Azimat Ojo Maghdub adalah wasiat tua, pesan leluhur yang terjaga. Pager urip, pagar hidup. Nikmat pitulungan, pertolongan yang jernih. Pitung turunan, keturunan yang selamat dari keruhnya kegelapan zaman. Karena sejatinya, hidup bukan soal seberapa lama kita bertahan, tapi seberapa lurus kita menjaga jalur cahaya di tengah keruhnya dunia.